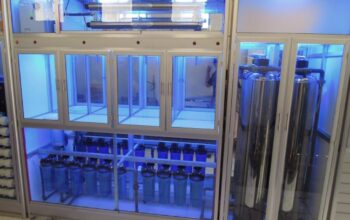DINAMIKA politik hukum Indonesia hari-hari ini menuai reaksi publik hingga demonstrasi mewarnai beberapa titik di Indonesia.
—
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.60/PUU-XXII/2024 Tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah oleh Partai Politik dan Putusan MK No.70/PUU-XXII/2024 Tentang Ketentuan Persyaratan Batas Usia Calon Kepala Daerah.
Sehari berselang, publik dikejutkan dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) No.10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang (UU) No.1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (PERPU) No.1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi UU (RUU Pilkada).
Sistem hukum Indonesia telah mengatur penyelenggaraan negara berdasarkan pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu, legislatif (membentuk UU), eksekutif (menjalankan UU yang dibentuk legislatif), dan yudikatif mengadili pelanggaran terhadap UU).
Pembagian kekuasaan itu bermaksud untuk saling mengawasi dan mengimbangi (checks and balances). Setiap lembaga mempunyai kewenangan dan kewenangan itu mempunyai batasan untuk mancapai kepastian, keadian dan kemanfaatan.
KEDUDUKAN DAN DAYA IKAT PUTUSAN MK
Kehadiran MK dilatarbelakangi oleh kebutuhan konstitusional suatu peradilan untuk menguji UU terhadap UUD.
Bermula dari pemikiran Hans Kelsen yang mengamini kehadiran suatu lembaga Verfassungsgerichtshoft atau Constitutional Court. MK memiliki tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 24 C UUD yang menyebutkan bahwa MK berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dimana putusannya bersifat final.
Kemudian dipertegas melalui UU No.8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No.24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang berwenang; Menguji UU terhadap UUD, Memutus sengketa kewenangan antar lembaga Negara, Memutus pembubaran partai politik dan Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
Putusan MK No.60/PUU-XXII/2024 menyatakan, Pasal 40 ayat 1 UU No.10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada) bertentangan dengan UUD.
Pasal yang dibatalkan oleh MK semula menyebutkan bahwa partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan paling sedikit 20% dari jumlah perolehan kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau 25% dari akumulasi suara sah.
Persentase persyaratan dukungan perolehan suara kini menjadi 6,5% sampai 10% sesuai dengan jumlah penduduk. Beleid ini cukup populistik dan demokratis.
Pembahasan RUU Pilkada di DPR merupakan tindak lanjut Putusan MK No.70/PUU-XXII/2024 yang bermuara pada penafsiran Putusan MK dan Putusan Mahkamah Agung (MA).
Putusan MA No.23P/Hum/2024 memutuskan syarat usia calon kepala daerah dihitung saat pelantikan calon terpilih. Sementara Putusan MK No.70/PUU-XXII/2024 memutuskan syarat usia calon kepala daerah dihitung saat penetapan pasangan calon.
Atas hal tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menghendaki penghitungan usia sesuai Putusan MA dan mengabaikan Putusan MK.
Putusan MA No.23P/Hum/2024 merupakan pengujian Pasal 4 ayat (1) Peraturan KPU (PKPU) No.9 Tahun 2020 yang merupakan peraturan di bawah UU. Sementara Putusan MK No.70/PUU-XXII/2024 menguji Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada. Secara hirarkis DPR menjalankan perintah pengujian UU, bukan pengujian PKPU untuk menjawab kepastian hukum Pilkada.
Sebagai lembaga negara yang berwenang menguji UU terhadap UUD, Putusan MK bersifat final and binding. Artinya sejak Putusan MK diucapkan dalam persidangan, maka secara otomatis berlaku dan mengikat semua pihak (erga omnes) dan tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh untuk membatalkan putusan tersebut.
DETERMINAN POLITIK TERHADAP PRODUK HUKUM
UU sejatinya merupakan produk politik, hal ini dapat dilihat dari karakteristik setiap produk UU yang dominan ditentukan oleh konfigurasi politik.
Hubungan hukum dan politik dapat diibaratkan seperti dua sisi dari satu keping uang logam, artinya hubungan di antara keduanya sangatlah erat dalam membicarakan penyelenggaraan negara dari tingkat pusat hingga daerah.
UU juga merupakan produk yang ditetapkan dengan melibatkan peran legislator ataupun co-legislator (legislative Acts). RUU atau UU yang disahkan oleh DPR harus berpedoman pada konsideran menimbang dan mengingat. Konsideran menimbang terkandung makna filosofis, politis dan sosiologis yang menjelaskan mengapa UU ini perlu direvisi.
DPR secara kelembagaan mempunyai Badan Legislasi (Baleg) sebagai subsistem yang koheren, terdiri dari 80 anggota perwakilan fraksi DPR untuk periode 2019-2024. Baleg DPR juga mempunyai wewenang untuk menjawab kebutuhan hukum (revisi) dengan berpedoman pada konsideran pembentukan perundang-undangan yang diharapkan jauh dari intervensi kekuasaan politik dan wajib mengedepankan kepentingan hukum yang populistik.
EFEK DOMINO
Pentingnya DPR untuk memahami konsideran menimbang, agar dapat mengetahui resiko politik terhadap masyarakat apabila RUU Pilkada disahkan. Di sisi lain ada konsideran mengingat yang mengandung makna yuridis.
Dalam konteks ini DPR perlu mempertimbangakan segala keputusan yang bersifat yuridis termasuk Putusan MK. Keputusan DPR tidak boleh menyimpangi Putusan MK dan prinsip-prinsip konstitusionalitasnya.
RUU Pilkada apabila disahkan, maka sangat rentan untuk digugat kembali ke MK dan memungkinkan untuk dibatalkan oleh MK demi menjaga kemurniaan konstitusi. Apalagi RUU Pilkada yang terkesan dipaksakan dan berpihak pada segelintir orang dan partai politik tertentu. DPR akan mengalami distrust dan kehilangan kodratnya sebagai lembaga pembentuk UU, karena determinan kekuasaan politik atas hukum sehingga mempengaruhi karakter produk hukum yang dihasilkan.
Baca Juga:
Mewujudkan Budaya Politik sebagai Alat Pemersatu; https://sentralpolitik.com/mewujudkan-budaya-politik-sebagai-alat-pemersatu/
Efek dominonya terhadap lembaga penyelengara dalam hal Komisi Pemilihan Umum (KPU) cukup berdampak. KPU mengalami kesulitan dalam proses penyusunan PKPU akibat ketidakpastian hukum dan ini sangat beresiko terhadap konfigurasi Pilkada. (*)